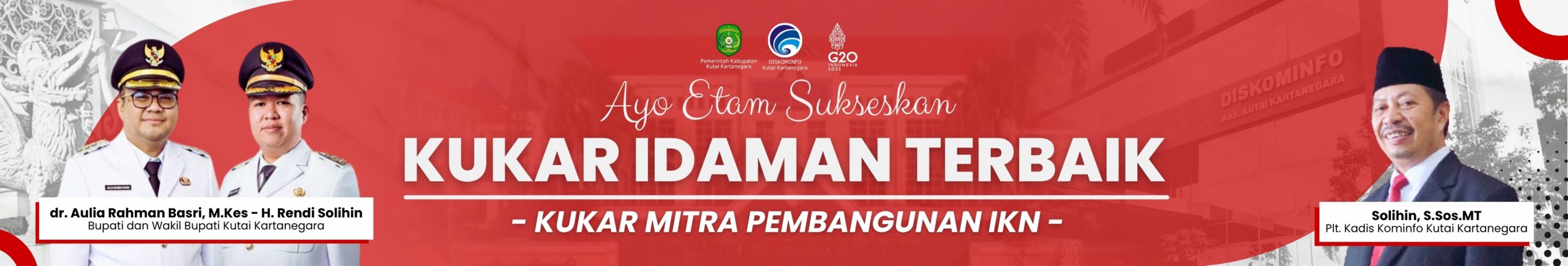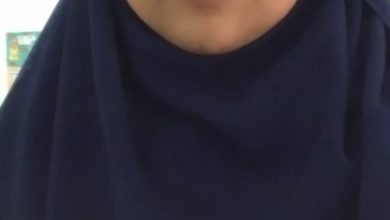Penulis : Imam Syahid, S.I.P., M.Sos
(Dosen Program Studi S1 Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Mulawarman)
Bujurnews.com, Samarinda – Pada pertengahan Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Pemerintah menilai perusahaan-perusahaan ini melakukan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan dan sebagian berada di kawasan lindung yang memiliki nilai konservasi tinggi.
Langkah ini langsung menuai respons positif dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat adat, organisasi lingkungan, hingga komunitas pariwisata. Raja Ampat bukan hanya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tetapi juga sebagai destinasi ekowisata yang menopang perekonomian lokal. Keputusan pemerintah untuk mencabut izin tambang di kawasan tersebut dianggap sebagai pesan kuat bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak dapat lagi dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Namun, keputusan ini bukan hanya soal teknis tata kelola tambang. Di baliknya, terdapat dinamika sosial politik yang kompleks, termasuk soal legitimasi kekuasaan, pertarungan kepentingan, dan keberlanjutan pembangunan.
Politik Lingkungan dan Tarik-Menarik Kepentingan
Pencabutan izin ini memperlihatkan bagaimana negara memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kajian politik lingkungan, negara sering menghadapi dilema klasik: mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Elinor Ostrom (2015) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan kepentingan politik. Tanpa aturan main yang jelas dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya cenderung dikuasai oleh elite politik dan ekonomi. Dalam konteks Raja Ampat, pencabutan izin dapat dipahami sebagai upaya pemerintah pusat untuk mereposisi dirinya sebagai aktor utama dalam mengatur relasi antara pemodal, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Namun, tanpa penguatan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas, kebijakan ini berisiko hanya menjadi simbolis. Seperti yang dikemukakan Douglas C North (1990) institusi yang lemah akan menghasilkan kebijakan yang mudah diintervensi oleh kepentingan jangka pendek dan tidak mampu menciptakan tata kelola yang stabil.
Keadilan Ekologis sebagai Prinsip Pembangunan
Dalam konsep keadilan lingkungan (environmental justice), kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kelompok yang paling rentan terdampak. Raja Ampat bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga rumah bagi masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem laut dan hutan untuk kehidupan sehari-hari. Prinsip keadilan ekologis menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Pencabutan izin tambang di kawasan konservasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemenuhan keadilan ekologis karena melindungi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses pembangunan. Selain itu, kebijakan ini memiliki dimensi politik yang erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan menurut Max Weber (1978) Dalam kerangka ini, tindakan pemerintah tidak hanya diukur dari efektivitasnya, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut memperkuat kepercayaan publik. Di tahun pertama pemerintahan, kebijakan spektakuler seperti pencabutan izin sering digunakan untuk membangun narasi bahwa pemerintah berpihak pada rakyat dan lingkungan.
Potensi Konflik dan Tantangan Implementasi
Meskipun menuai apresiasi, kebijakan ini menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, dari perspektif negara hukum, kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak mudah digugat. Beberapa perusahaan dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme peradilan dengan alasan kepastian hukum, terutama jika izin mereka diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan geopark internasional. Kedua, pencabutan izin dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi. Pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Jika pencabutan izin tidak diiringi program transisi ekonomi yang jelas, masyarakat lokal bisa kehilangan mata pencaharian dan memicu konflik sosial. Ketiga, pengawasan terhadap perusahaan yang masih beroperasi merupakan ujian kredibilitas pemerintah. Jika pengawasan dilakukan secara tidak transparan, akan muncul persepsi adanya politik pilih kasih. Hal ini sejalan dengan konsep good governance, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap proses kebijakan.
Keputusan ini juga merefleksikan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam teori masyarakat sipil, masyarakat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dan modal. Selama bertahun-tahun, berbagai LSM lingkungan, akademisi, tokoh adat, dan media telah mendorong perlindungan ekosistem Raja Ampat melalui kampanye dan advokasi publik. Pencabutan izin tambang ini dapat dipahami sebagai hasil dari tekanan kolektif tersebut. Namun, partisipasi deliberatif menurut Jurgen Habermas (1989) mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap protes. Negara perlu menyediakan ruang dialog yang berkelanjutan, di mana keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam diambil secara inklusif dan transparan. Tanpa mekanisme ini, masyarakat sipil akan kembali menjadi pihak pasif yang hanya mengkritik tanpa memiliki pengaruh dalam kebijakan.
Rekomendasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
Agar kebijakan ini membawa perubahan nyata, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, Meningkatkan transparansi dalam perizinan. Akses publik terhadap informasi izin dan status kawasan konservasi akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik perizinan yang bermasalah. Menyiapkan program transisi ekonomi. Pengembangan ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pelatihan keterampilan baru menjadi penting agar masyarakat lokal tidak kehilangan mata pencaharian. Membentuk mekanisme pengawasan independen. Pengawasan yang melibatkan akademisi, LSM, dan tokoh adat akan memperkuat integritas kebijakan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Menyusun peta jalan nasional pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik antar kepentingan.
Pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat merupakan langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan negara kepada lingkungan dan masyarakat adat. Kebijakan ini memiliki makna ganda, yaitu sebagai pemenuhan prinsip keadilan ekologis dan sebagai strategi politik untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Namun, keberlanjutan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan inklusif. Dengan tata kelola yang baik, keputusan ini dapat menjadi preseden positif bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada retorika, kebijakan ini akan kehilangan makna dan kepercayaan publik akan merosot. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi bujurnews.com
Daftar Pustaka
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. In Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press.
Ostrom, E. (2015). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. In Canto Classics. Cambridge University Press.
Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press.